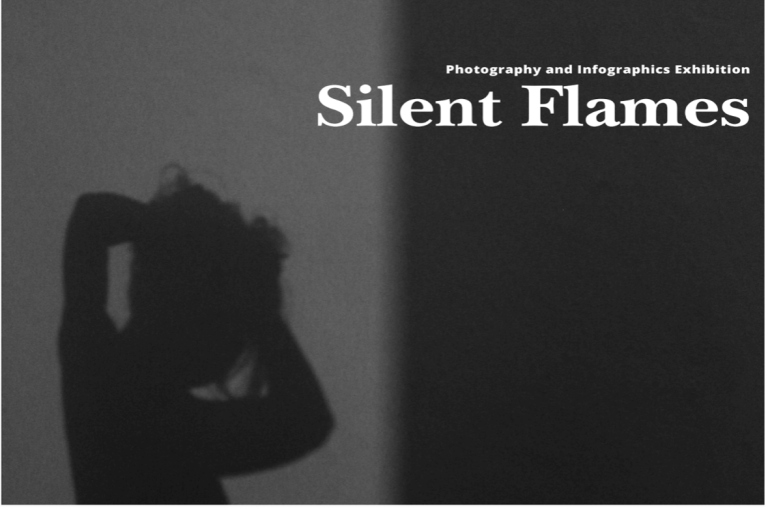
Suara. Ia bermuka dua. Di satu sisi membawa pencerahan. Di sisi lain menambah kebisingan. Gegap gempita internet dan media sosial awalnya dianggap sebagai ‘teknologi pembebasan’, yang mampu memberdayakan mereka yang tersingkir. Namun kini, ruang publik itu turut diisi oleh buzzer dan siapapun yang tidak membawa nilai. Ruang yang riuh rendah tanpa arah.
Padahal, suara seharusnya memuat nilai. Kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan adalah nilai substansial, yang memungkinkan kita bersuara atas tuntunan tersebut. Tampaknya di titik inilah perbedaannya: antara suara yang mencerahkan dan suara yang membisingkan. Dalam hal ini, saya mengartikan suara dan nilai dalam satu tarikan napas.
Tetapi, banyak yang menganggap suara Gen Z sebagai suara yang bising dan belum matang. Suara generasi ini seolah sekadar keluhan dan rengekan. Pekikan yang jauh panggang dari api. Malahan frasa ‘Suara Gen Z’ layaknya oksimoron, suatu frasa yang kontradiksi dalam dirinya sendiri. Seperti, pahit manis, hidup mati, panas dingin, dan sebagainya. Ia ada sekadar untuk menimbulkan penekanan dan efek retoris semata. Singkatnya, suara Gen Z dianggap hanya keras, tapi tak bermakna.
Sangkaan tersebut mungkin sekali datang dari mereka yang tak mau dengar. Namun, program studi Kajian Budaya dan Media (KBM), Universitas Gadjah Mada memedulikannya. Melalui acara pameran fotografi dan infografis, generasi yang tumbuh besar di era digital ini menyerukan anti-diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Ruang pameran visual Silent Flames tidak hanya menampilkan luka, tetapi juga pesan yang kuat. Dan dari cara membicarakan karyanya, suara Gen Z sarat akan nilai. Ajakan untuk menjenguk nurani. Suaranya bukan oksimoron. Ia menyadarkan, bukan menyingkirkan. Ia seruan perlawanan, bukan celotehan.

Estafet Perlawanan
Suara perlawanan memang identik dengan budaya anak muda, dari protes Mei 1968 di Prancis, demonstrasi menentang Perang Vietnam dan Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat, gerakan Occupy Wall Street, Arab Spring hingga Black Lives Matter. Bahkan perjuangan kaum muda Indonesia memainkan peran penting dalam trajektori revolusioner, semenjak masa kolonial hingga 1998. Suara kaum muda mempunyai rekam jejak yang kental dalam gerak perubahan sosial. Mereduksi pemuda sekadar kata kunci angkatan generasi bagaikan sayur tanpa garam. Itu melucuti kekuatan militansinya. Dari konteks sosial, dari kondisi kultural, terhadap relasi kuasa yang timpang, dan seterusnya.
Belakangan banyak nama yang bisa disebutkan. Misalnya, Greta Thunberg, remaja berusia 15 tahun yang pada tahun 2018 memulai gerakan membolos sekolah demi memperjuangkan lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan School Strike for Climate. Sebelumnya juga ada Emma Watson saat berusia 25 tahun menjadi proponen kampanye HeForShe, gerakan solidaritas global untuk kesetaraan gender. Dan seterusnya dan seterusnya.

Namun tak bisa disimpulkan persoalan-persoalan tersebut telah lenyap. Suara mereka bergema kini justru karena kesadaran akan problem sosial yang mengakar. Adanya relasi sosial yang ganjil, bahkan di ruang yang Gen Z akrabi selama ini: ruang digital. Di satu sisi, memang teknologi meresonansi tuntutan mereka menjadi lebih lantang daripada sebelumnya. Di sisi lain, persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender turut mengental. Memunculkan krisis nilai dan moral.
Di tengah hiruk pikuk krisis yang akut, karya-karya di ruang pameran Silent Flames menjelma estafet perlawanan terhadap normalisasi persoalan. Bahwa say no to discrimination and gender based violence telah menjadi semacam bendera generasi saat ini demi kehidupan sosial yang lebih beradab. Silent Flames, api yang membakar dengan sunyi sekaligus memercik. Dan percikan itu diteruskan dari suluh satu ke suluh yang lain. Seperti itulah suara perlawanan. Ia adalah tekad yang esensial pada generasi. Sejak dulu hingga nanti.

Kontributor: Zainul Arifin
SDG 5, SDG 10
